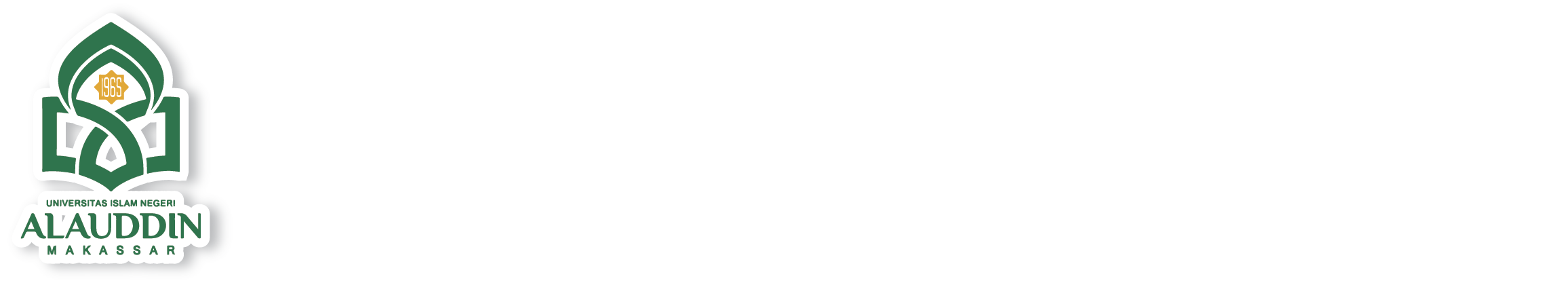Di sejumlah grup WA ramai didiskusikan pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani bahwa guru adalah beban negara. Pernyataan itu beredar sejumlah platform media sosial, dan masif bergerak ke seluruh grup WhatsApp dan tentu saja pernyataan menuai banyak kecaman. Hanya saja pertanyaannya adalah apakah pernyataan itu benar bersumber dari Menteri keuangan atau justru diproduksi oleh hasil kecerdasan buatan (AI).
Kasus video manipulatif ini menjadi salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk membelokkan realitas. Video itu sekilas tampak meyakinkan, penuh dengan potongan gambar yang menyusun alur seolah-olah wajar. Bagi orang yang hanya menonton sekali, bisa jadi ia langsung percaya, apalagi jika memang sudah ada bias emosional terhadap tokoh yang bersangkutan. Namun setelah diverifikasi oleh banyak media arus utama, bahwa itu jelas rekayasa, sebuah deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan narasi palsu. Tempo, Detik, Liputan6, CNN Indonesia, hingga Kompas telah menegaskan bahwa video tersebut hoaks. Bahkan TurnBackHoax menggunakan perangkat deteksi konten sintetis dan hasilnya jelas bahwa video itu adalah manipulasi. Sri Mulyani pun mengklarifikasi langsung bahwa ia tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, bahkan pidatonya sama sekali berbeda konteks.
Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa dunia digital bukan hanya ruang untuk berbagi, tetapi juga ruang yang penuh jebakan. Jika dahulu hoaks hadir dalam bentuk tulisan dengan tanda baca yang berantakan atau bahasa provokatif, kini hoaks bisa datang dalam bentuk video yang rapi, suara yang mirip, bahkan ekspresi wajah yang sangat meyakinkan. Inilah yang disebut era post-truth, ketika fakta bisa dikaburkan oleh ilusi, dan kebenaran dapat tertutup oleh persepsi yang sengaja dibentuk. Celakanya, banyak orang masih lebih cepat percaya ketimbang memeriksa. Sebuah video yang viral sering dianggap lebih sahih daripada klarifikasi dari sumber resmi.
Padahal, kerentanan ini bisa berdampak sangat luas. Bayangkan menjelang Pemilu, di mana suhu politik memanas, lalu muncul video deepfake seorang kandidat yang menyebut lawannya dengan kata-kata kasar atau melontarkan pernyataan sensitif tentang SARA. Satu potongan video saja bisa menyalakan api kebencian, membuat masyarakat saling curiga, bahkan memicu kerusuhan. Hoaks dalam bentuk teks saja sudah cukup membahayakan, apalagi jika dibungkus dalam format audiovisual yang tampak begitu nyata.
Maka dari itu, literasi informasi menjadi perisai yang paling penting. Literasi informasi bukan sekadar kemampuan membaca atau menonton berita, melainkan keterampilan berpikir kritis, memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta mengendalikan emosi ketika menerima kabar yang memancing marah atau sedih. Literasi informasi berarti tidak tergesa-gesa percaya, tidak buru-buru membagikan, dan tidak gampang terseret arus opini. Literasi informasi juga mengajarkan bahwa klarifikasi bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Orang yang mau memeriksa kebenaran justru menunjukkan kedewasaan.
Di tengah derasnya arus teknologi, kita juga perlu menyadari bahwa kecerdasan buatan bersifat netral. Ia bisa menjadi berkah bila digunakan untuk pendidikan, penelitian, kesehatan, dan inovasi. Namun ia bisa berubah menjadi ancaman bila dipakai untuk menyebarkan kebencian atau menebar fitnah. Dalam kasus deepfake Sri Mulyani, AI digunakan sebagai senjata untuk merusak reputasi dan menggiring opini. Di sinilah letak tantangan baru bagi masyarakat: bagaimana tetap memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dalam manipulasi yang ia hasilkan.
Refleksi yang bisa kita petik adalah bahwa demokrasi dan kebebasan informasi akan kehilangan makna jika masyarakat tidak membekali diri dengan daya kritis. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi. Tanpa literasi, kebebasan justru menjadi bumerang, karena ruang publik dipenuhi kebisingan yang menyesatkan. Jika kita lengah, kita akan menjadi masyarakat yang mudah diprovokasi, mudah dipecah belah, dan sulit bersatu.
Menghadapi situasi ini, setiap individu punya peran. Kita bisa mulai dari hal sederhana: menunda jari sebelum membagikan, menunda mulut sebelum menyebarkan, dan menunda hati sebelum percaya. Kita bisa membiasakan diri mengecek media arus utama, mencari konfirmasi dari pihak terkait, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Kita juga bisa mengingatkan orang-orang di sekitar agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi.
Kasus ini memberi pesan penting bahwa di zaman ketika mata bisa dibohongi oleh layar, akal sehat dan hati nurani adalah saringan terakhir. Tidak semua yang tampak nyata adalah benar, dan tidak semua yang viral adalah fakta. Tugas kita adalah belajar untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memahami. Tidak hanya mendengar, tetapi juga mencari bukti. Tidak hanya bereaksi, tetapi juga merefleksi.
Pada akhirnya, literasi informasi adalah tentang keberanian untuk bersikap kritis sekaligus bijak. Kita tidak bisa menghentikan teknologi berkembang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi korban. Jika masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif ini, maka deepfake secanggih apapun hanya akan berakhir sebagai permainan ilusi, bukan sebagai kebenaran palsu yang menguasai pikiran kita.
Samata 22 Agustus 2025