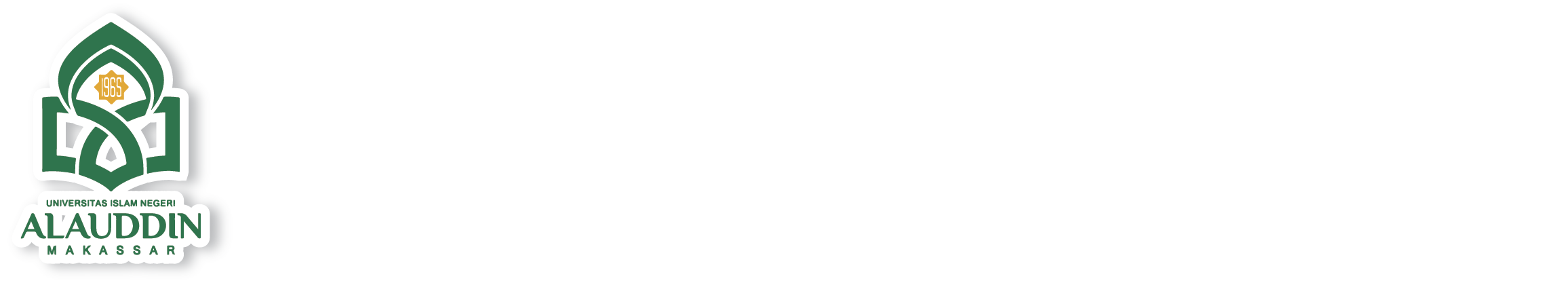"Kami menggulirkan program penguatan ekoteologi menitikberatkan pada aksi iklim untuk mencegah kerusakan alam yang berangkat dari pemahaman keagamaan,” demikian ungkap Menag RI Prof. Dr. Nasruddin Umar, MA saat menerima penghargaan (award) Penggerak Nusantara 2025.
Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan panggilan moral yang menempatkan agama kembali pada poros kemanusiaan dan kealaman. Di tengah eskalasi krisis iklim global, ketika suhu bumi meningkat, ekosistem runtuh, dan bencana ekologis menjadi rutin, gagasan menautkan teologi dengan tindakan ekologis adalah langkah strategis sekaligus visioner. Ekoteologi hadir bukan sebagai konsep pinggiran, tetapi sebagai jembatan antara spiritualitas, etika, dan tanggung jawab sosial terhadap bumi.
Dalam pandangan banyak ahli, termasuk Thomas Berry dan Seyyed Hossein Nasr, kerusakan alam bermula dari krisis spiritual, manusia menjauh dari makna sakral alam semesta. Berry menyebut bumi sebagai “komunitas kehidupan,” bukan sekadar sumber daya yang dieksploitasi. Nasr menegaskan bahwa kehilangan pandangan kosmologis dalam tradisi keagamaan membuat manusia tercerabut dari kesadaran ekologisnya. Kesadaran inilah yang ingin dihidupkan kembali melalui program penguatan ekoteologi yang digagas Kementerian Agama bahwa spiritualitas bukan hanya berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tentang relasi yang harmonis dengan ciptaan-Nya.
Dalam Islam, konsep harmoni ekologis bukan hal baru. Al-Qur’an berulang kali menyebut alam sebagai ayat-ayat Tuhan. Gunung, laut, angin, dan tumbuhan bukan sekadar objek fisik, melainkan tanda yang mengajar manusia tentang keseimbangan. Ketika manusia melampaui batas dan merusak keseimbangan ini, maka kerusakan di darat dan laut muncul akibat ulah tangan mereka. Di sinilah ekoteologi bekerja, membaca kembali teks agama dengan sensitivitas ekologis, agar keyakinan melahirkan perilaku ekologis. Tidak cukup hanya memahami konsep khalifah, tetapi mengeksekusinya dalam kebijakan, gaya hidup, dan budaya baru yang ramah bumi.
Pernyataan Menag menjadi relevan karena krisis ekologis bukan sekadar isu ilmiah, tetapi juga persoalan etika. Sosiolog Ulrich Beck menyebut era ini sebagai “masyarakat risiko,” di mana bahaya ekologis yang kita hadapi sebagian besar berasal dari ulah manusia sendiri. Maka aksi iklim membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga moral. Perlindungan lingkungan membutuhkan kesediaan manusia untuk menahan diri, menata ulang gaya hidup konsumtif, dan mengakui bahwa bumi bukan milik generasi sekarang saja.
Aksi ekoteologi menempatkan harmoni sebagai inti dari keberagamaan. Harmoni ini bukan sekadar keadaan tanpa konflik, tetapi sebuah kesadaran untuk hidup selaras dengan ritme alam. Beberapa pemikir Islam kontemporer menekankan konsep mizan (keseimbangan) sebagai prinsip teologis yang wajib dijaga. Ketika keseimbangan bumi terganggu, maka tugas spiritual manusia adalah memulihkannya. Pendekatan ini menjadikan ibadah tidak hanya ritual, tetapi juga ekologis, menanam pohon menjadi bagian dari iman, mengurangi sampah menjadi bentuk ketakwaan, dan melindungi satwa menjadi ekspresi syukur.
Dalam konteks Indonesia, ekoteologi memiliki relevansi yang semakin mendesak. Negara ini kaya secara hayati, tetapi sekaligus rentan, deforestasi, polusi sungai, eksploitasi tambang, dan krisis air menjadi ancaman yang nyata. Program Menag bisa menjadi kekuatan pendorong bagi ormas keagamaan, pondok pesantren, kampus, hingga masyarakat luas untuk menjadikan isu lingkungan sebagai agenda spiritual dan sosial. Ketika lembaga-lembaga keagamaan mengarusutamakan ekoteologi, narasi publik tentang lingkungan akan berubah dari isu teknis menjadi panggilan iman.
Lebih jauh, harmoni dalam ekoteologi mengajarkan bahwa penyelamatan planet tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral. Ia membutuhkan kerja kolektif lintas agama, ilmu pengetahuan, dan kebijakan publik. Para ahli ekologi menyebut konsep earth solidarity, solidaritas bumi, yang menempatkan semua makhluk sebagai bagian dari jejaring kehidupan yang saling terkait. Ekoteologi memperkuat gagasan ini melalui landasan spiritual bahwa menyakiti alam sama dengan merusak amanah Tuhan.
Pernyataan Menag sesungguhnya mengajak masyarakat Indonesia memasuki babak baru keberagamaan, agama yang tidak hanya membicarakan keselamatan jiwa, tetapi juga keselamatan bumi. Harmoni ekologis menjadi bagian dari misi spiritual. Melalui ekoteologi, manusia tidak lagi memandang alam sebagai objek, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan spiritual. Di tengah tantangan krisis iklim, pendekatan ini bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pionir ekoteologi global: sebuah bangsa yang menggabungkan iman, ilmu, dan aksi demi menjaga rumah besar kehidupan. Dengan demikian, program penguatan ekoteologi bukan sekadar kebijakan, melainkan komitmen jangka panjang untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih memiliki bumi yang layak dihuni, bumi yang hidup dalam harmoni.
Sungguminasa 22 Nopember 2025