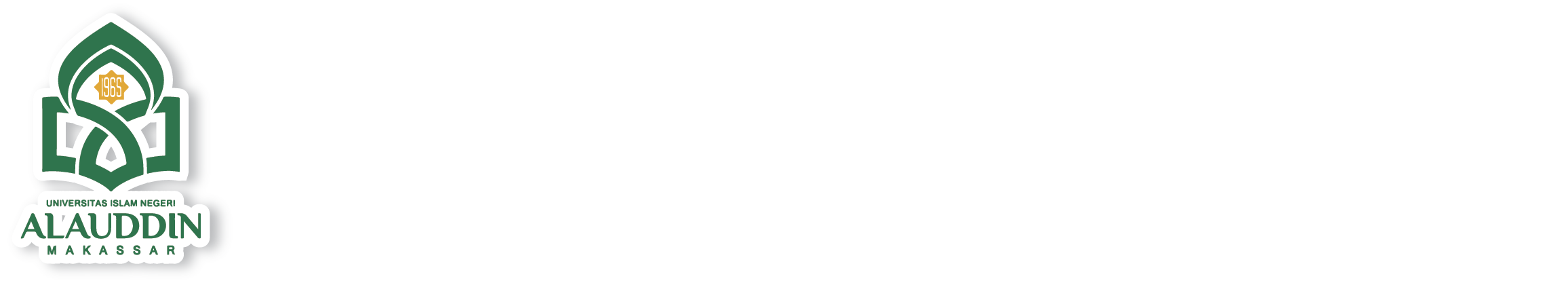Pagi itu, Senin 28 Juli 2025, dua Asesor BAN-PT untuk salah satu prodi di UIN Alauddin Makassar diterima secara resmi di ruang rapat rektor. Seperti biasa Prof. Hamdan, rektor UIN Alauddin Makassar dengan segala kepandaian retorika dan canda humor berkelas mampu menghangatkan suasana penyambutan sehingga lebih cair.'
Saat salah satu asesor diberikan kesempatan menyampaikan sambutan, dia menceritakan pengalaman ketika dibawa keliling kampus UIN Alauddin yang sangat megah dan bersih ini. Pendamping asesor itu menjelaskan bahwa kampus ini dahulu adalah *HUTANG*.
Asesor itu hanya manggut-manggut. Di dalam pikirannya menyeruak segudang tanya...sebanyak apa hutang dan dimana UIN berutang sehingg bisa berdiri kampus semegah ini.?
Asesor kemudian baru sadar setelah dijelaskan bahwa di Makassar, huruf n itu dibaca ng. Kata *hutan*, dibaca hutang. Jadi maksudnya, kampus Samata itu dahulunya adalah *hutan**. Mendengar cerita asesor itu, kami pun tertawa lepas.
Mendengar true story yang lucu ini, salah seorang unsur pimpinan UIN Alauddin ikut sharing pengalaman saat berhadapan dengan seorang pejabat perbankan perempuan yang berasal dari luar Sulsel, dan belum mengenal bahasa daerah.
Dengan percaya diri dan di bawah kontrol alam bawah sadar, dia bertanya...*Dimana kita tidur/ menginap*? Tentu saja dia kaget. Bayangkan jika anda seorang perempuan luar Sulsel yang belum tahu bahasa lokal ditanya oleh seorang laki-laki dengan pertanyaan seperti itu?
Inilah salah satu potret bagaimana fonetik lokal dan pengucapan dialektik bisa menjadi jebakan makna yang menyesatkan. Di berbagai daerah Indonesia, banyak kata yang jika diucapkan oleh penutur lokal akan terdengar sangat berbeda dari makna sesungguhnya dalam bahasa Indonesia standar. Contoh jika anda berada di Banjarmasin dan ingin membeli bola lampu, cukup bilang ke penjaga toko...Pak saya mau beli listrik. Tapi kalimat ini tidak bisa dipakai di Makassar, penjaga toko akan kebingungan mendengar orang mau beli listrik.
Di Makassar cukup bilang *mau beli balon*
Kalimat...*mau beli balon* ini juga, bisa membuat orang Banjarmasin salah paham. Jika itu yang diucapkan, maka yang keluar adalah *Koki-koki* (istilah Makassar untuk mainn anak-anak kecil)
Fenomena ini kerap terjadi bukan karena kesalahan bahasa, melainkan karena adanya sistem bunyi khas yang terbentuk dalam komunitas tutur tertentu.
Bahasa daerah menyimpan kekayaan fonologis yang unik. Di Makassar, misalnya, kata “kita” sering berarti “kamu”, sementara dalam bahasa Indonesia, makna tersebut menunjuk pada “kita semua”. Perbedaan ini tidak sekadar semantik, melainkan juga mengandung risiko sosial terutama jika digunakan dalam komunikasi antardaerah yang tidak akrab dengan logat lokal. Kesalahpahaman pun tak terhindarkan.
Kesalahpahaman ini menjadi menarik jika ditelusuri dari sisi linguistik, terutama fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, sedangkan fonologi melihat bagaimana bunyi itu berfungsi dalam suatu sistem bahasa. Dalam interaksi antarbudaya, distorsi fonetik seperti ini bisa memicu kebingungan, terutama bagi pendengar yang tidak familiar dengan logat tersebut.
Tak hanya masalah pengucapan, makna juga bergeser karena interpretasi sosial terhadap bahasa. Bahasa adalah produk budaya, dan dalam budaya yang kaya dialek seperti Indonesia, setiap kata membawa ruang tafsir yang lebar. Bahkan satu kata bisa bermakna lain tergantung siapa yang mengucapkan dan dalam konteks apa kata itu muncul. Ketika makna dibaca secara literal tanpa pemahaman latar kultural, di situlah sering terjadi miskomunikasi.
Dari fenomena ini dipahami bahwa komunikasi bukan sebatas bahasa sebagai sistem bunyi, tetapi soal empati dan niat. Seorang komunikator yang bijak akan berusaha memahami bukan hanya kata yang diucapkan, tetapi juga makna yang dimaksudkan oleh lawan bicara. Ia akan bertanya sebelum menghakimi, menyimak sebelum menyanggah, dan memverifikasi sebelum menanggapi.
Dalam tradisi Islam, komunikasi bukan hanya tindakan teknis, tetapi juga bagian dari akhlak. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ucapan yang baik tidak hanya dilihat dari isi katanya, tetapi juga dari efeknya pada orang lain. Kesantunan bahasa, termasuk upaya memahami keragaman logat dan bunyi, adalah bagian dari adab dalam berbicara.
Jangan sampai karena lidah, hati menjadi luka. Jangan sampai hanya karena salah ucap, kita menutup telinga dari maksud baik orang lain. Ketika kita mampu menempatkan niat di atas bunyi, dan memahami maksud di balik kata, maka kita sedang menjalankan pesan luhur agama, membangun hubungan yang damai, memahami sebelum disalahpahami, dan menjembatani perbedaan melalui akhlak komunikasi.
Jumat 1 Agustus 2025
Barsihannor