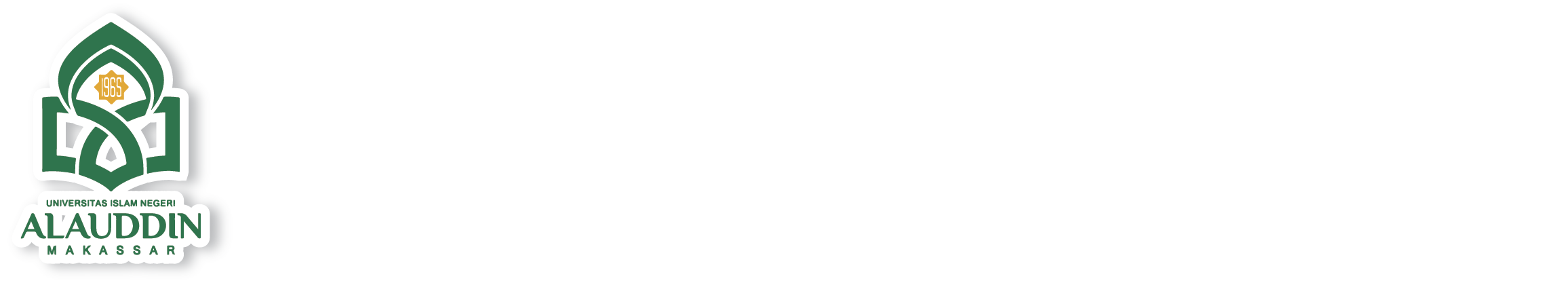Menurut survey, netizen Indonesia menempati peringkat ke 5 netizen paling cerewet di dunia. Tapi dari sisi kemampuan literasi, Indonesia berada justru di urutan no 71.
Apa yang disampaikan di survey itu tampaknya diperkuat dengan fenomena komentar nitizen di berbagai platform media sosial. Komentar itu kadang asal, tidak berdasar, hanya berdasarkan selera personal, bahkan kadang bernada bullying. Saya meyakini bahwa mereka yang berkomentar itu adalah mereka yang memiliki agama, tapi nilai religiusitas belum tercermin dalam kehidupan.
Inilah salah satu ironi terbesar dalam kehidupan beragama dewasa ini, terutama di kalangan Gen Z yang akrab dengan digitalisasi dan akrab dengan media sosial. Simbol-simbol keagamaan, dari pakaian, slogan dakwah, hingga status WhatsApp bertuliskan ayat suci begitu ramai. Namun, kehadiran nilai-nilai yang seharusnya menjadi ruh dari simbol itu, kerap justru menghilang dalam praktik keseharian.
Di TikTok, misalnya, kita bisa melihat remaja berjilbab yang mengunggah konten bernada religius, namun di video lain ikut melakukan body shaming atau menyebar ujaran kebencian atas nama menjaga agama. Ada yang fasih bicara soal dalil, tapi gagal menerjemahkannya dalam empati, dialog, dan akhlak sosial.
Krisis ini bukan soal kurangnya pengetahuan, melainkan karena pemutusan antara simbol dan implementasi. Agama kerap berhenti pada tampilan luar pakaian, jargon, dan ritual tanpa menyentuh kedalaman makna seperti kejujuran, toleransi, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.
Padahal, dalam tradisi Islam sendiri, Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa agama itu bukan sekadar simbolik, melainkan akhlak. Pakaian menutup aurat adalah baik, tapi tak cukup jika lidah masih menyakiti. Membaca al-Qur’an itu mulia, tapi tak berguna jika tidak diterjemahkan ke dalam tindakan yang adil, bijak, dan penuh kasih.
Fenomena ini tak lahir dari ruang kosong. Gen Z hidup dalam dunia visual dan instan, dimana simbol lebih cepat viral daripada substansi. Budaya performatif (melakukan sesuatu agar terlihat, bukan karena makna) menjangkiti cara beragama. Akibatnya, keimanan yang seharusnya menumbuhkan kasih justru dipakai sebagai alat validasi ego atau identitas kelompok.
Karena itu, perlu pendekatan pendidikan agama yang menekankan etika dan spiritualitas, bukan sekadar ritual dan simbol. Ajaran agama harus dipahami secara holistik bahwa memakai simbol keagamaan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menjadi manusia yang lebih adil, rendah hati, dan penyayang.
Perlu pula ada ruang dialog yang sehat di dunia digital. Tokoh agama, konten kreator muslim, dan komunitas keagamaan harus hadir menyuarakan makna di balik simbol, bukan sekadar memperbanyak simbol itu sendiri. Gen Z harus diajak berpikir bukan hanya tentang "apa yang kamu pakai?", tetapi "apa yang kamu pancarkan?"
Simbol keagamaan bukanlah masalah, bahkan sangat diperlukan. Namun, simbol yang bisu yang tak diiringi implementasi nilai bisa menjadi sekadar topeng. Dan ketika agama hanya jadi topeng, maka yang tersisa hanyalah kebisingan tanpa kebijaksanaan.
Sungguminasa 7 Juli 2025