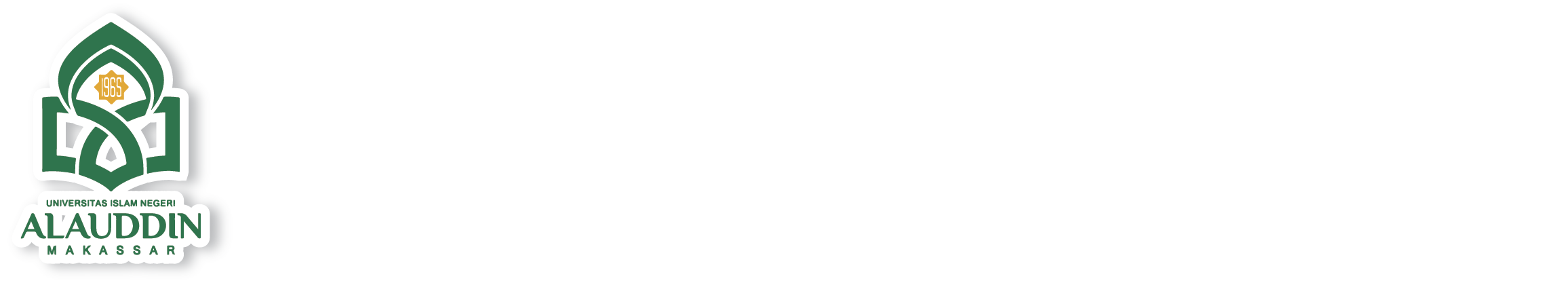Tawa bisa menyembuhkan luka, tapi ia juga bisa menorehkan luka baru terutama ketika lahir dari ketidaktahuan. Inilah yang terjadi ketika narasi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono menyentuh wilayah paling sakral dalam kebudayaan Toraja yaitu tradisi pemakaman. Dengan nada bercanda dia menyebut tradisi rambu Solo bisa mendatangkan kemiskinan. Sebuah humor yang mungkin dimaksud sebagai hiburan di atas panggung, tiba-tiba menjelma menjadi bara kontroversi yang menyulut amarah kolektif masyarakat Tana Toraja.
Bagi sebagian penonton di luar konteks budaya, ucapan Pandji mungkin hanya sekadar lelucon. Namun bagi masyarakat Toraja, tradisi pemakaman bukan sekadar prosesi sosial, ia adalah ritual sakral yang mengikat nilai-nilai spiritual, historis, dan identitas kultural. Tradisi “Rambu Solo’” misalnya, bukan sekadar upacara kematian, tetapi simbol penghormatan tertinggi terhadap kehidupan dan leluhur. Di sanalah jiwa budaya Toraja bersemayam. Maka ketika sakralitas itu dijadikan bahan komedi, rasa tersinggung yang lahir bukan sekadar reaksi emosional, tapi jeritan hati yang merasa disalahpahami.
Budaya menurut antropolog Clifford Geertz (1973) adalah “webs of significance,” jaring makna yang menuntun manusia memahami dunia dan dirinya sendiri. Artinya, setiap simbol, upacara, bahkan bahasa tubuh dalam kebudayaan memiliki lapisan makna yang mendalam. Melecehkannya, meski dalam konteks bercanda, berarti merobek jaring makna yang membentuk eksistensi sebuah komunitas. Dalam konteks Toraja, budaya bukan sekadar tradisi, melainkan heart of life, jantung kehidupan yang memompa identitas dan spiritualitas warganya dari generasi ke generasi.
Di sinilah pentingnya memahami sakralitas budaya. Sakralitas bukan hanya milik agama, banyak kebudayaan mengandung dimensi transenden yang tidak kalah suci dari nilai keagamaan. Mircea Eliade (1959), seorang filsuf agama, menjelaskan bahwa yang sakral bukan hanya apa yang disebut agama, tetapi segala hal yang dianggap memiliki nilai tertinggi dalam kosmos manusia. Dengan kata lain, ketika masyarakat memuliakan leluhur, tanah, atau upacara adatnya, mereka sedang mengekspresikan rasa religi dalam bentuk kultural.
Toraja adalah salah satu contoh kuat dari pemaknaan itu. Upacara kematian bukan sekadar penghantaran arwah, melainkan komunikasi spiritual antara dunia kini dan dunia arwah, sebuah harmoni antara manusia, leluhur, dan semesta. Ketika tradisi ini dijadikan bahan tawa, maknanya bukan sekadar menertawakan upacara, tetapi juga menertawakan sistem nilai yang menopang keberadaan mereka. Itulah sebabnya masyarakat Toraja merasa dihina—karena bagi mereka, yang diserang bukan kebiasaan, tapi kesakralan hidup.
Dalam dunia seni dan komedi, kebebasan berekspresi tentu sangat dijunjung. Namun, kebebasan tanpa empati hanyalah bentuk lain dari arogansi intelektual. Komedi yang cerdas bukan yang menertawakan perbedaan, melainkan yang menertawakan keseragaman, bukan yang merendahkan yang lain, tapi yang mengajak berpikir dengan ringan. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana setiap suku memiliki nilai yang suci, sensitivitas budaya bukanlah batas, melainkan etika moral dalam berkarya.
Edward T. Hall (1976) mengingatkan bahwa setiap kebudayaan memiliki ruang diam (silent language) yaitu nilai-nilai yang tidak diucapkan tetapi sangat hidup. Menyentuhnya tanpa pengetahuan mendalam dapat memicu kesalahpahaman yang luas. Komika, seniman, atau siapa pun yang berkarya di ruang publik seharusnya memiliki literasi budaya yang cukup agar tak terjebak dalam kekeliruan serupa.
Peristiwa ini seharusnya menjadi refleksi kolektif, bukan sekadar ajang saling menyalahkan. Masyarakat bisa mengambil hikmah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan makna budayanya, sementara para pekerja seni perlu belajar bahwa humor bukan alasan untuk menihilkan nilai-nilai yang dianggap suci oleh orang lain.
Kita memang hidup di era globalisasi, tapi tidak berarti kita harus menertawakan akar kita sendiri. Budaya adalah denyut nadi bangsa, tanpanya, kita hanya tubuh tanpa jiwa. Maka, ketika sebuah tradisi dijadikan bahan olok-olok, sejatinya yang dipertaruhkan bukan hanya harga diri satu etnis, tetapi martabat kemanusiaan itu sendiri.
Mari belajar tertawa dengan hati, bukan dengan menginjak hati orang lain. Sebab, di balik setiap tawa yang lahir dari penghinaan, ada air mata peradaban yang mengering.
Dan barangkali, sebagaimana pepatah Toraja berkata, “To menani’ to tuppu’,” manusia sejati adalah mereka yang tahu menempatkan hormat pada yang hidup dan yang telah tiada.
Menghargai kearifan lokal adalah cara paling bijak untuk menjaga kemanusiaan tetap beradab.
Sungguminasa 3 November 2025